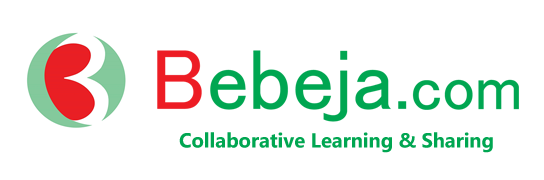Puluhan bakul bersepeda itu datang dan berkumpul di satu tempat. Mereka menunggu kedatangan mobil pembawa telur puyuh dari Yogyakarta. Saat mobil datang, 220.000 telur puyuh segera berpindah tangan. Melalui bakul-bakul itu perjalanan telur puyuh berlanjut ke berbagai sudut kota.
Itu pemandangan pagi hari di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sekitar 20 tahun lalu. Kebutuhan besar telur puyuh di kabupaten seluas 1.812 km2 itu, mendorong tumbuhnya peternak puyuh lokal seperti di Desa Datinawong, Kecamatan Babat. Seiring waktu warga Desa Datinawong mulai menggantungkan hidup dari beternak puyuh, selain kerajinan mainan anak.
Kondisi itu mulai meredup seiring krisis ekonomi pada 1998. Harga pakan melonjak tajam mencapai Rp125.000 per 25 kg. Normal, harga pakan itu tak lebih dari Rp30.000. Wajar efeknya besar, sejumlah peternak gulung tikar. Saat itu tetasan puyuh umur sehari atau DOQ (Day of Quail) yang dibagikan gratis pun tidak ada yang mau.
Imbas kejadian itu, tidak hanya dijumpai di Lamongan, tapi juga melebar ke sentra puyuh lain seperti di Yogyakarta dan Sukabumi, Jawa Barat. Namun memasuki 2000-an, beberapa peternak di sentra-sentra itu mulai bangkit. Mereka memulai memelihara puyuh skala kecil dengan populasi sekitar 2.000 ekor. Dari jumlah itu rata-rata bisa dipanen 1.500 telur/hari dengan harga jual Rp60-65/butir.
Sampai medio 2005, peternak puyuh terus tumbuh. Siswanto di Yogyakarta, misalnya memanen hingga 2.000 telur dari populasi 2.500 puyuh. Ia merawat puyuh di 9 kandang berukuran 4 m x 0,3 m x 0,4 m. Omzet bersih penjualan setelah dipotong biaya produksi sekitar Rp2-juta/bulan. Siswanto memasok pasar di Yogyakarta dan sesekali mengirim ke Bandung dan Cirebon. Untuk luar kota, mencapai 300 dus dengan isi setiap dus 750 telur.
Siswanto juga memperoleh pasokan dari 7 peternak lain untuk menjamin kontinuitas. Saat itu pasar di luar Pulau Jawa seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali belum tergarap. Pendapatan Siswanto bertambah setahun setelah memelihara puyuh lantaran puyuh memasuki masa penurunan produksi alias apkir. Harga puyuh apkir mencapai Rp1.200-Rp1.500/ekor. Pasarnya rumah makan dan restoran penyedia menu puyuh.
Sejatinya, budidaya puyuh di Indonesia berlangsung sejak 1970-an seiring perkembangan peternakan ayam ras petelur. Sayang, perkembangan selanjutnya stagnan lantaran berbagai faktor seperti bobot telur puyuh kecil, hanya 10-12 gram/butir atau 1/5 dari bobot telur ayam.
Dengan kondisi itu sulit bagi telur puyuh memenuhi kebutuhan industri roti, kue, dan penganan lain. Pemanfaatannya hanya sebagai campuran sup atau menu sate di warung bubur ayam dan angkringan. Belum lagi kondisi fisik telur ringkih karena berkulit tipis. Itu berdampak pada cara kemas, terutama pengiriman jarak jauh.
Meski begitu, beternak puyuh tetap memiliki keunggulan seperti dapat diusahakan di lahan sempit. Peternak bisa membudidayakan puyuh di lahan 20 m2 dengan populasi 2.000-2.500 ekor. Bayangkan populasi sama untuk ayam ras petelur, butuh hingga 20-30 kali luasan sama. Sudah begitu investasi puyuh juga rendah.
Ongkos pembuatan kandang kapasitas 1.000 ekor sekitar Rp700.000. Untuk puyuh siap telur harga Rp4.000-Rp5.000 tergantung kualitas penangkar. Singkat kata, untuk beternak 1.000 puyuh butuh modal Rp9-juta-Rp10-juta selama setahun. Dengan masa bertelur hingga 12 bulan, dari 1.000 ekor dengan produksi 750 telur/hari, total jenderal bisa dipanen sekitar 273.000 telur.
Dengan harga jual minimal Rp60/butir, peternak bisa meraup omzet Rp16,3-juta/tahun. Itu belum menghitung pendapatan lain dari penjualan burung apkir sebesar Rp2,4-juta dengan asumsi minimal harga Rp1.200/ekor.