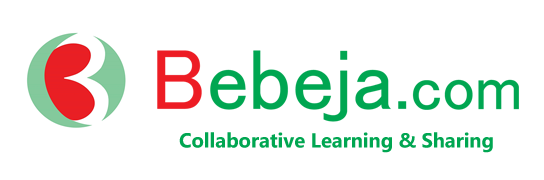Tiga sekawan Fred S Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Scramm boleh melontarkan empat teori pers, tapi Indonesia tak pernah mengakui sebagai penganut satu di antaranya.
Pers Indonesia telah menyatakan diri bukanlah Authoritarian Press, Libertarian Press, Social Responsibility Press, dan Soviet Communist Press seperti yang mereka bertiga ungkap dalam Fourth Theories of The Press.
Dalam sejarahnya, pers Indonesia telah mengalami keempat model pers ala tiga sekawan itu, bahkan sejak “Memoria der Nouvells” surat kabar tulisan tangan pertama yang terbit padad abad ke-17 di era pendudukan Hindia Belanda.
Pers authoritarian sempat singgah di tanahair pada masa keemasan VOC. Pun social responsibility press pernah diterapkan pada masa orde baru meski pada kenyataannya pemerintah terlampau represif menghadapi media, serta libertarian press terjadi pada awal era reformasi sebagai bentuk euforia pers pascalepas dari kekangan selama puluhan tahun.
Sementara soviet communist press yang merupakan gabungan libertarian dan social responsibility pers sempat juga diterapkan dalam satu dekade meski pada prakteknya tidak benar-benar memenuhi aturan yang disyaratkan. Namun, apapun teori yang dikemukakan, pada dasarnya konsep pers di Indonesia adalah unik dengan berbagai dinamika isu, kebijakan pemerintah, hingga masyarakat yang melingkupinya.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers di Indonesia masih jauh dari impian jurnalisme ideal ala Bill Kovach, tapi betapa dinamisnya media di tanahair yang selalu menarik untuk dikaji. Kesejahteraan wartawan sebagai profesi yang dipandang elit dan intelek belum juga memadai, mengingat masih ada perusahaan media yang membayar reporter di bawah UMR bahkan hingga detik Hari Pers Nasional (HPN) 2014.
Meski wakil ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai pers nasional telah mengalami kemajuan secara kuantitas dan kualitas, sehingga sudah seharusnya mereka yang dilatih dengan baik, diberi peralatan yang baik, dan digaji dengan baik dan cukup. “Dalam konteks ini, maka sangat ironis jika masih ada pekerja pers yang digaji rendah, di bawah UMR, dan masih jauh sekali dari kesejahteraan minimal,” katanya. Padahal, pers masih menjadi pilar keempat demokrasi, di mana demokrasi akan kuat manakala pers kuat.
“Pers yang kuat adalah pers yang didukung oleh nilai idealisme kuat, tidak berpihak kecuali pada kebenaran, perusahaan pers yang kuat, lingkungan budaya yang kondusif, situasi politik yang terbuka, dan pekerja pers yang profesional,” katanya. Akhirnya, wartawan yang belum jua sejahtera itulah yang membuat kaum terdidik itu kreatif, memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Amplop adalah isu yang wajar, menggarap proyek-proyek instansi adalah konsekuensi kedua, hingga menjalin sindikat penyeragaman konten (sindikasi berita) seringkali memaksa hal itu terjadi. Wartawan kemudian dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya menjalani pekerjaan sebagai profesi sekaligus sebagai buruh dari perusahaannya, moral dan perut adalah pilihan yang sulit.
Pers Indonesia adalah unik, memang tak bisa dipungkiri apalagi keberadaannya yang bukan pada ruangan hampa. Sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial yang berlaku di Indonesia memberikan pengaruh yang nyata terhadap pers. Dalam sejarah menjelang reformasi, misalnya pergolakan pers untuk membebaskan diri dari kungkungan rezim yang represif begitu keras luarbiasa.
Pers Indonesia menuntut ditegakkannya diri mereka sebagai pilar keempat demokrasi, watchdog, yang mengontrol jalannya pemerintah sesuai dengan namanya “press” yang berarti menekan. Namun sampai saat itu kemudian terpenuhi, insan pers sendiri yang mengingkari, memborgol tangan sendiri dan menyerahkannya kembali pada pemerintah sebagai mitra pembangunan. Ini adalah contoh sindikasi media di level yang lebih tinggi ketika headline dan halaman dengan mudah diseragamkan dari sisi konten, satu komando untuk satu kepentingan terselubung.
Di sisi lain kini, pers di tanahair sedang menghadapi problem independensi dan objektifitas dalam politik pemberitaan dan pemberitaan politik. Bahkan, masyarakat dengan mudahnya bisa menyaksikan masuknya para penguasa media ke dalam ranah politik praktis. Isu kepemilikan media dan konflik kepentingan kemudian menjadi pekerjaan rumah ketika politik demokrasi yang sedang dipraktikkan di Indonesia adalah politik yang berdasarkan sistem pemilihan langsung dan demokrasi deliberatif.
Politik semacam itu jelas sangat mengutamakan popularitas tokoh, mengarusutamakan pencitraan, dan mendewakan pembentukan opini, dimana peran media bukan hanya sangat besar, melainkan juga sangat menentukan. Di luar itu, pers kemudian dituntut untuk tetap tidak kehilangan nurani, independensi, dan obyektifitas dalam politik berita dan berita politik.
Ketua DPR Marzuki Ali berpendapat pers harus bisa melihat dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar. “Pers bebas namun bertanggung jawab, mampu melihat dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar,” katanya.
Isu besar yang menjadi tantangan serius bagi pers Indonesia adalah konglomerasi media besar-besaran. Pers adalah industri yang sarat kepentingan sehingga conflict of interest, media ownership, agenda setting, hingga pembunuhan karakter bercampur menjadi satu wadah yang harus diemban pers merah putih. Setidaknya, pers di Indonesia telah membuktikan pameo lama ala media mogul Rupert Murdoch, “Siapa yang menguasai media dialah penguasa dunia”.
Nyatanya, kehebatan media di tanahair dalam membentuk opini publik yang boleh jadi syarat dengan kepentingan tak diragukan lagi. Presiden SBY dalam akun twitternya menuliskan: “Kontrol pemilik media dan kekuasaan sama buruknya terhadap demokrasi,” menjadi cermin betapa pemerintah mengharapkan independensi pers.
Padahal peran pers di negara demokrasi sangat penting sebagai perantara dan penyampai informasi, tetapi monopoli dan konglomerasi media yang terpusat pada segelintir pihak membuat informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi bias dan cenderung penuh deviasi. Hal itu berbahaya lantaran tugas pers tidak hanya menjadi penyampai informasi namun juga harus menjadi kontrol sosial agar kondisi masyarakat tetap terkendali sekaligus mengedukasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring setengah menuntut agar idealisme pers jangan sampai dirusak oleh kalangan industri dan jangan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bisnis semata. “Kita harus mengingatkan kembali idealisme pers, jangan sampai dirusak oleh kalangan industri, yang dipikirkan hanya keuntungan semata,” kata Tifatul.
Menurut Tifatul, ke depan sudah seharusnya pers Indonesia menjadi pers yang sehat demi mendukung rakyat yang berdaulat. Menteri sekaligus berharap agar pers tidak menjadi alat politik bagi partai tertentu. Solusi kemudian ditawarkan, meski terdengar klise tapi pers perlu dikembalikan pada pondasi etik, hukum, dan kemampuan melaporkan yang baik. Pers harus berpegang teguh pada peraturan baik itu undang–undang, ataupun kode etik jurnalistik yang sudah ada.
Di lain pihak, pemerintah juga harus turut andil dalam menata industri pers yang hanya dikuasai segelintir orang saja, jangan segan turun tangan untuk mengeluarkan peraturan tentang kepemilikan perusahaan pers. Bahkan, Amerika Serikat sebagai nenek moyang pers liberal pun memiliki peraturan yang melarang monopoli kepemilikan media. Jadi akankah pers Indonesia lebih Amerika dari Amerika itu sendiri? (Hanni Sofia).
 Riwayat Penulis: Hanni Sofia adalah master art of journalism dari Ateneo de Manila University. Saat ini ibu 3 anak itu adalah pewarta ekonomi di desk ekonomi mikro meliputi kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UKM dan tekno di Kantor Berita Antara di Jakarta. Perempuan yang sudah 9 tahun berkecimpung di dunia pers dan sangat menggemari jalan-jalan itu saat ini adalah kontributor www.bebeja.com.
Riwayat Penulis: Hanni Sofia adalah master art of journalism dari Ateneo de Manila University. Saat ini ibu 3 anak itu adalah pewarta ekonomi di desk ekonomi mikro meliputi kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UKM dan tekno di Kantor Berita Antara di Jakarta. Perempuan yang sudah 9 tahun berkecimpung di dunia pers dan sangat menggemari jalan-jalan itu saat ini adalah kontributor www.bebeja.com.