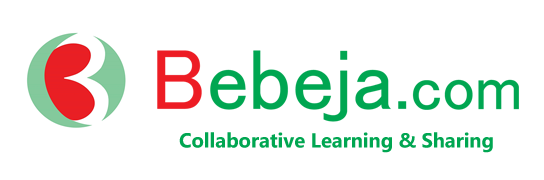Hutan Indonesia mempunyai tingkat biodiversitas tinggi. Indonesia memang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati di dunia selain Brasil, Kolombia, dan Zaire. Dengan luas darat mencakup 1,3% dari total luas daratan dunia, Indonesia menyimpan 30.000-35.000 jenis tumbuhan.
Jatna Supriatna PhD dalam buku Melestarikan Alam Indonesia menyebutkan, Provinsi Papua di ujung timur Indonesia memiliki keragaman tumbuhan tertinggi, mencapai 19.000-20.000 jenis. Pulau Jawa dan Sumatera menjadi rumah bagi 10.000 dan 14.000 jenis tumbuhan.
Dari 30.000-35.000 tumbuhan tersebut, sekitar 4.000 (13,3%) di antaranya merupakan pohon kayu. Dari ribuan jenis pohon kayu itu, 400 jenis pohon telah dimanfaatkan seperti Agathis Agathis spp atau kayu damar.
Kayu damar, kayu kelas awet III dan kelas kuat IV itu merupakan bahan baku kotak peti, korek api, pensil, kayu lapis, dan mebel. Jenis lainnya bangkirai Shorea laevifolia. Tumbuhan yang dipanggil kerangan di Sumatera itu populer untuk konstruksi pada jembatan, bantalan, tiang layar, dan lunas perahu.
Data Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan-kini Kementerian Kehutanan RI-mengungkapkan, Indonesia memiliki 3.124 jenis kayu yang terbagi ke dalam beberapa kelompok, yakni kayu komersial, nonkomersial, kayu budidaya, dan tidak dikenal.
Jenis kayu nonkomersial dan tidak dikenal memiliki bobot jenis (BJ) rendah, tidak kuat, dan tidak awet, sehingga pemanfaatannya terbatas. Contohnya kayu balsa Ochroma spp, randu Ceiba pentandra, kemiri Aleurites moluccana, dan merkubung Macaranga sp. Kayu balsa misalnya, memiliki nilai BJ 0,15-0.28 (skala 0-1). Bandingkan dengan kayu jati dengan nilai BJ antara 0,62-0,75.
Kayu dari kelompok Dipterocarpaceae seperti keruing Dipterocarpus spp di hutan di Sumatera dan Kalimantan paling diminati industri. Kayu-kayu itu istimewa karena nilai BJ mencapai 0,7-0,8 sehingga tergolong kategori kayu kuat I-II dan awet III. Itu artinya kayu-kayu tersebut cocok untuk bahan konstruksi. Sebab itu, di Kalimantan, separuh dari 350 jenis anggota Dipterocarpaceae dieksploitasi secara masif.
Mayoritas kayu itu diperoleh dari hutan di dataran rendah maupun tinggi. Apabila usaha penebangan kayu-kayu itu diiringi penanaman bibit lagi, penebangan tidak menjadi masalah. Yang terjadi justru setelah tebang, hutan malah gundul.
Dampaknya seperti terjadi di Kalimantan Tengah pada 1977. Saat itu permukaan air Sungai Barito naik hingga 8 meter. Kenaikkan itu memicu menghancurkan 6.600 ha lahan pertanian dan bencana bagi 20.000 penduduk. Hal tersebut efek penebangan 1,12-juta ha oleh 13 perusahaan HPH (hak penguasaan hutan) yang abai penanaman lagi.
Data Strategis Kehutanan 2009 menyebutkan, luas hutan Indonesia mencapai 133,8-juta ha. Keberadaan hutan sesungguhnya bernilai penting. Dari berbagai riset diketahui, 1 ha hutan menyerap 10 ton/tahun gas karbon. Faktanya laju deforestasi sulit dihindari. Yang paling memungkinkan adalah membatasi.
Hingga 2020 laju deforestasi akan dipertahankan 1,125-juta hektar/tahun. Sementara laju hutan terdegradasi akibat pembalakan luasnya dipertahankan 626.000 hektar/tahun. Isu perdagangan karbon tengah mencuat 4-5 tahun terakhir ini lantaran pelepasan karbon memicu perubahan iklim global.
Jumlah karbon Indonesia sungguh luarbiasa. Polusi karbon di tanahair sudah disejajarkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Mengapa bisa? Sumber utama polusi karbon di tanahair adalah lahan gambut. Kalimantan Tengah dengan luas lahan gambut sekitar 3-juta hektar menyimpan karbon setara 22 gigaton CO2.
Bila lahan gambut itu dikonversi menjadi lahan pertanian, potensi terlepas CO2 ke udara sangat besar. Maka dari itu tak heran bila Bank Dunia menyebutkan kebakaran gambut pada 1997-1998 sebagai salah satu dari 10 bencana terbesar di dunia di abad ke-20.
Setiap hektar lahan gambut menampung hingga 2.600 ton CO2 yang terbentuk dari daun, ranting, atau buah yang berguguran selama ribuan tahun. Di lahan gambut itu lantaran terendam air, bahan organik tersebut tak sempat membusuk, lalu tertimbun bahan organik mati lain di atasnya. Padahal, seluruh karbon di atmosfer diserap oleh pohon di hutan melalui proses fotosintesis.
Melalui mekanisme Reducing Emmissions from Deforestation and Degradation (REDD), hutan mutlak dipelihara untuk menjaga agar karbon di atmosfer tak lepas kendali. Sampai kini mekanisme model penghitungan karbon dan pemberian insentif terus dibahas antara negara maju dan negara berkembang, sebagai pemilik hutan.
Bagaimana strategi agar sumber kayu hutan lestari? Tak pelak, perlu membangun hutan tanaman industri (HTI). Hingga awal 1980-an, 3 negara Asia, yakni Korea Selatan, Indonesia, dan Taiwan merupakan produsen kayu lapis terbesar dunia yang menguasai 70% pangsa pasar kayu lapis dunia.
HTI yang dirintis sejak 1960, meski populer pada 1980 merupakan jawaban. Pada 2000, luas HTI mencapai 6,2-juta hektar. HTI disarankan karena mudah dilakukan dengan sistem monokultur. Jenis pilihan untuk HTI seperti akasia, eukaliptus, albisia, dan mahoni. Diperkirakan produksi HTI menyumbang 90-juta m3 kubik kayu bulat per tahun. Jumlah itu mampu menyelamatkan hutan alami Indonesia dari pembalakan liar.